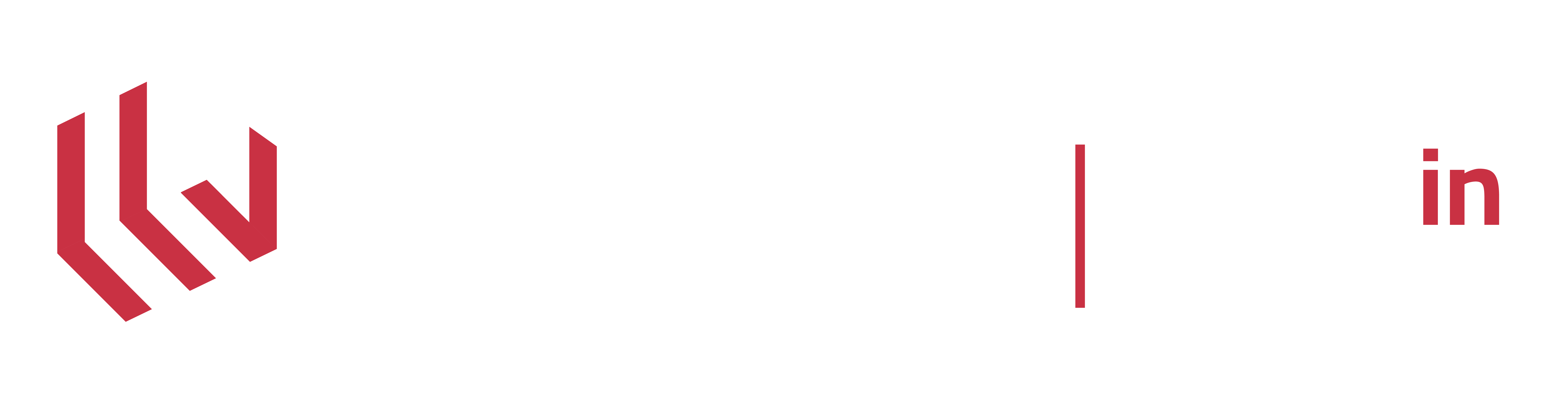Oleh: Azmul Fauzi, S.Pd. | Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
LINEAR.CO.ID | BANDA ACEH – Kita sedang hidup dalam zaman yang disebut oleh banyak pemikir sebagai era post-truth, atau “era setelah kebenaran”. Dalam dunia seperti ini, emosi dan opini pribadi sering kali lebih kuat pengaruhnya daripada fakta dan data. Informasi yang paling sering dibagikan bukanlah yang paling benar, tetapi yang paling menggugah perasaan.
Fenomena ini semakin jelas terlihat di Indonesia. Isu-isu sosial, politik, agama, bahkan kesehatan sering kali menjadi bahan adu klaim kebenaran di media sosial. Hoaks beredar begitu cepat, membentuk persepsi publik yang kadang jauh dari kenyataan. Akibatnya, masyarakat tidak hanya mengalami disinformasi, tetapi juga krisis epistemik krisis dalam cara kita memahami dan memaknai kebenaran.
Untuk memahami situasi ini secara mendalam, kita perlu meninjau kembali persoalan kebenaran dari sudut filsafat ilmu, yang secara klasik membahas tiga dimensi pokok: ontologi (hakikat realitas), epistemologi (cara memperoleh pengetahuan), dan aksiologi (nilai serta tujuan penggunaan pengetahuan). Ketiganya memberikan peta pikir yang dapat menuntun kita keluar dari kabut kebingungan informasi di era digital.
Ontologi: Kebenaran di Tengah Realitas Virtual
Secara ontologis, kita perlu bertanya: apa yang sebenarnya dimaksud dengan kebenaran di zaman digital ini?
Dalam pandangan klasik filsafat, seperti yang dikemukakan Aristoteles, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan (correspondence theory of truth). Artinya, sebuah informasi dianggap benar jika sesuai dengan fakta yang ada di dunia nyata.
Namun, di era digital, batas antara dunia nyata dan dunia maya menjadi kabur. Algoritma media sosial menciptakan ruang realitas baru yang sering kali tidak mencerminkan kenyataan sesungguhnya. Apa yang kita lihat di layar bukan lagi cerminan objektif dunia, tetapi hasil seleksi dari sistem algoritmik yang dirancang untuk menarik perhatian, bukan untuk mencari kebenaran.
Misalnya, ketika terjadi peristiwa politik atau bencana, berbagai narasi yang bertentangan muncul bersamaan di dunia maya. Masing-masing kelompok memproduksi “kebenarannya sendiri” lengkap dengan bukti, data, dan tafsir yang mendukung. Maka, realitas digital tidak lagi bersifat tunggal, melainkan plural dan terfragmentasi.
Secara ontologis, kita menghadapi situasi di mana kebenaran kehilangan pijakan objektifnya. Ia berubah menjadi sesuatu yang dikonstruksi sosial tergantung siapa yang berbicara, di mana ia berbicara, dan kepada siapa informasi itu disebarkan. Inilah akar dari krisis kebenaran modern.
Epistemologi: Krisis dalam Cara Kita Mengetahui
Setelah memahami hakikatnya, kita perlu menelaah secara epistemologis : bagaimana sebenarnya manusia memperoleh pengetahuan di tengah banjir informasi ini?
Dalam tradisi ilmu pengetahuan, proses memperoleh kebenaran menuntut sikap kritis, pengujian, dan verifikasi. Ilmu berkembang melalui metode ilmiah, yang menekankan kejujuran intelektual dan keterbukaan terhadap koreksi. Namun di dunia digital, mekanisme epistemologis ini digantikan oleh kecepatan dan popularitas.
Kita hidup dalam budaya klik dan bagikan (click and share culture), di mana informasi tidak diuji, hanya disebarkan. Orang lebih percaya pada apa yang sejalan dengan keyakinannya (konfirmasi bias) daripada mencari kebenaran objektif. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis masyarakat semakin menurun, digantikan oleh pola pikir instan yang hanya ingin tahu “siapa yang benar”, bukan “apa yang benar”.
Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai isu publik dari vaksinasi, politik identitas, hingga konflik sosial. Banyak orang lebih mempercayai pesan berantai di WhatsApp atau potongan video di TikTok dibanding laporan resmi atau riset akademik. Ini bukan semata masalah teknologi, tetapi masalah epistemologi: kita kehilangan kemampuan untuk memverifikasi kebenaran.
Maka solusi epistemologis yang mendesak adalah pendidikan literasi digital dan literasi ilmiah. Masyarakat harus dilatih untuk memeriksa sumber, memahami konteks, dan menilai kredibilitas informasi. Sekolah, universitas, dan media massa perlu berperan aktif menumbuhkan budaya berpikir kritis dan etika informasi.
Kebenaran di era digital tidak akan ditemukan oleh mereka yang paling cepat membagikan informasi, tetapi oleh mereka yang paling sabar memeriksa kebenaran informasi itu.
Aksiologi: Untuk Apa Kebenaran Digunakan?
Aspek ketiga dari filsafat ilmu adalah aksiologi, yakni nilai dan tujuan pengetahuan.
Di sinilah pertanyaan moral muncul: untuk apa kebenaran digunakan?
Idealnya, pengetahuan dipergunakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik menumbuhkan keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Namun dalam realitas digital, pengetahuan sering kali disalahgunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, bahkan kebencian. Banyak aktor digital dari influencer hingga lembaga besar menggunakan data dan algoritma untuk membentuk opini publik sesuai kepentingan mereka. Dalam dunia yang serba dikendalikan logika pasar dan klik, nilai kebenaran sering kali dikorbankan demi popularitas.
Di sinilah pentingnya refleksi aksiologis: pengetahuan tanpa nilai moral akan kehilangan arah.Sebagaimana diingatkan oleh filsuf Jürgen Habermas, komunikasi publik seharusnya diarahkan pada “tindakan komunikatif” yaitu dialog yang bertujuan mencapai pemahaman bersama, bukan sekadar memenangkan perdebatan.
Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sangat penting. Ketika perbedaan politik atau agama disulut oleh disinformasi, maka tugas moral kita adalah mengembalikan nilai ilmu dan pengetahuan kepada fungsi kemanusiaannya: menyatukan, bukan memecah-belah.
Relevansi Filsafat Ilmu di Tengah Kekacauan Informasi
Jika kita memandang lebih luas, krisis kebenaran hari ini sebenarnya menunjukkan betapa pentingnya filsafat ilmu. Di tengah hiruk pikuk informasi digital, filsafat ilmu mengajarkan kita untuk kembali berpikir mendasar: apa itu kebenaran, bagaimana ia diperoleh, dan untuk apa ia digunakan.
Filsafat ilmu tidak hanya relevan bagi kalangan akademik, tetapi juga bagi masyarakat luas. Bagi akademisi, ia menjadi pengingat agar riset dan pengetahuan tidak tercerabut dari nilai moral dan sosial. Bagi jurnalis, ia menjadi dasar untuk menjaga integritas informasi di tengah tekanan pasar digital.Bagi masyarakat umum, ia menjadi panduan untuk tidak mudah percaya, tetapi berani berpikir dan bertanya.
Dengan kata lain, filsafat ilmu mengajak kita untuk menyeimbangkan tiga hal: fakta, logika, dan etika. Ketiganya harus berjalan bersama agar kebenaran tidak menjadi korban dari kepentingan atau sensasi.
Membangun Etika Kebenaran di Era Digital
Krisis kebenaran di era digital bukan sekadar masalah teknologi, melainkan masalah cara manusia memperlakukan pengetahuan. Ketika kita lebih mementingakan kecepatan daripada ketepatan, popularitas daripada kebenaran, dan opini daripada data maka sesungguhnya kita sedang menggerogoti dasar peradaban ilmu itu sendiri.
Melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, filsafat ilmu memberikan arah bagi kita untuk keluar dari krisis ini. Secara ontologis, kita diingatkan agar tidak kehilangan kesadaran akan realitas objektif. Secara epistemologis, kita dituntun untuk menumbuhkan budaya verifikasi dan berpikir kritis. Dan secara aksiologis, kita diajak untuk menggunakan pengetahuan demi kemanusiaan dan keadilan sosial.
Seperti kata Karl Popper, “Ilmu bukan sekadar kumpulan pengetahuan, melainkan sikap kritis terhadap pengetahuan itu sendiri.” Maka di tengah kebisingan digital, menjaga kebenaran bukan hanya tugas ilmuwan, tetapi tanggung jawab moral setiap manusia berakal.